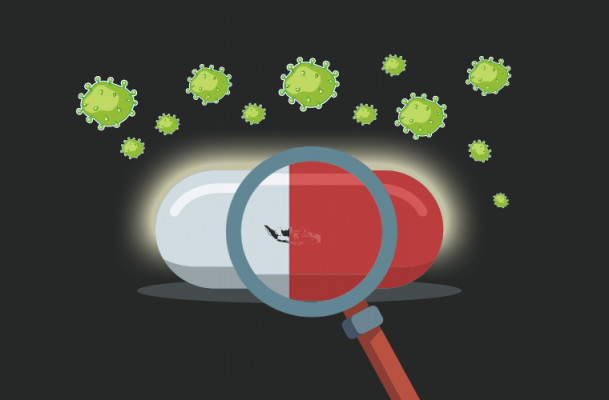
Semua tahu: belum ada obat untuk Covid-19. Tapi apakah pasien tidak perlu diobati?
Para dokter pasti berada dalam dilema yang luar biasa. Lalu harus membuat keputusan. Dokter tidak boleh terus menerus dalam keraguan.
Saat akhirnya membuat keputusan dokter sudah memikirkannya berdasar keahliannya. Bukan berdasar perintah atau instruksi atau tekanan.
Itulah sebabnya pekerjaan dokter disebut ‘profesi’. Bukan pekerjaan biasa. Mereka harus punya ilmu di bidang itu dan harus punya otonomi untuk membuat keputusan.
Sampailah dokter pada putusan: harus diberi obat apakah pasien ini. Padahal obat untuk Covid-19 belum ada.
Mungkin juga dokter sudah tahu ada obat yang lebih baik dari itu. Apalagi di zaman internet ini. Dokter-dokter muda langsung tahu perkembangan terbaru di dunia luar.
Tapi apakah obat yang lebih baik itu sudah ada di Indonesia?
Maka saya bisa memaklumi dokter akan memberi obat apa pun yang menurut mereka terbaik di antara yang tersedia.
Saya pun mendapat info penting ini: di sebuah rumah sakit di Jakarta pasien Covid-19 diberi obat Oseltamivir 2x 75 mg. Ditambah vitamin C. Juga Azithromycin 2×500 mg atau Levofloxacin 1×750 mg.
Bagi pasien yang sudah agak berat ditambah Chloroquine sulphate 2x 500 mg.
Lalu ditambah lagi obat lain berdasar penyakit lain yang ditemukan di pasien Covid-19.
Misalnya ditambah Hepatoprotektor bagi pasien yang punya masalah liver. Misalnya SGPT/SGOT-nya tinggi.
Mungkin dokter di rumah sakit lain berbuat lain lagi. Atau sama. Sesuai dengan keilmuan dan otonomi mereka.
Yang lebih pusing adalah presiden –terlihat dari sikap Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia harus membuat keputusan tapi tidak punya ilmunya.
Dan keputusan itu harus bisa sekalian mendongkrak popularitasnya. Presiden harus terlihat jagoan di situasi krisis seperti ini.
Maka Trump mendeklarasikan diri sebagai ‘Presiden di masa Perang’. Dan ia harus memberi semangat rakyatnya untuk optimistis.
Lalu harus pula bisa menutup kesan bahwa ia sangat telat dalam menangani krisis Covid-19 ini.
Untuk menutup kelemahan itu ia carilah kambing hitam. Sekaligus banyak: Gubernur New York, Partai Demokrat, dan Tiongkok.
Untuk menggerakkan optimisme dan semangat rakyat ia pun berpidato dengan gagah: sudah menemukan obat untuk Covid-19. Sudah bisa langsung diproduksi. Hanya karena ia maka prosedur izin produksinya bisa dipercepat. Soal perizinan beres.
Pokoknya rakyat segera dapat obatnya.
Nama obat itu: Chloroquine. Dan Hydroxychloroquine.
Hah?
Semua ahli obat lantas menertawakannya –dalam hati. Juga di medsos.
Nama obat yang disebut Trump yang pertama itu adalah obat produksi tahun 1940-an.
Itu adalah obat malaria.
Trump ngotot bahwa FDA sudah mengesahkannya sebagai obat Covid-19. Wartawan pun mendesaknya: kapan persetujuan itu diberikan?
Dijawab: pokoknya sudah disetujui.
Maka FDA pun buru-buru klarifikasi. Dengan cara yang halus. “FDA sedang mengkajinya,” ujar pemimpin tertingginya.
Mungkin Trump memang tidak pernah kena malaria. Sehingga tidak begitu kenal dengan nama Chloroquine. Juga tidak tahu apa saja efek sampingannya. Terutama terhadap pendengaran dan mata.
Ahli di Amerika sendiri sudah lama sekali menyempurnakan Chloroquine dengan produk baru: Hydrochloroquine.
Tapi seorang presiden memang harus mengambil keputusan. Seperti juga dokter yang tidak mungkin membiarkan pasiennya tergeletak menunggu begitu saja datangnya obat yang belum ditemukan itu.
Begitu juga Presiden Indonesia Jokowi. Harus membuat keputusan: membeli jutaan obat bikinan Jepang, Avigan. Yang sebenarnya juga bukan obat Covid-19.
Trump kali ini memang terlihat panik. Kecaman membanjiri ke alamatnya. Termasuk dari internal partainya.
Ia sudah beda sekali dengan dua bulan lalu. Saat Covid-19 sudah meluas di Tiongkok. Saat itu Trump ditanya wartawan: mungkinkah covid-19 menjadi pandemik.
“Tidak. Sama sekali tidak,” jawabnya.
Ketika ditanya bukankah sudah ada penduduk Amerika yang mulai terkena, Trump tetap kekeuh. “Itu kan hanya satu orang yang datang dari Tiongkok,” ujarnya.
Sampai sekarang yang sudah nyata-nyata melakukan uji coba obat Covid-17 barulah Tiongkok dan Amerika.
Tiongkok melakukannya Februari lalu. Obat itu disuntikkan kepada dokter dan perawat militer yang ditugaskan di rumah sakit khusus darurat di gedung olahraga Wuhan.
Hasilnya: sampai tugas mereka selesai minggu lalu tidak satu pun dokter dan perawat militer itu yang tertular.
Tapi, normalnya, obat itu masih harus melewati banyak uji coba lagi. Terutama untuk menentukan ada tidaknya efek samping dan serapa banyak dosis yang diperlukan.
Mayjen Chen Wei, ilmuwan wanita yang mengepalai proyek penemuan obat Covid-19 itu Sabtu kemarin memberikan keterangan baru.
Percobaan lanjutan sudah dilakukan kepada relawan dari tiga kota: Wuchang, Hongshan, and Donghu Scenic Area. Semuanya di sekitar Wuhan.
Percobaan itu dilakukan dalam tiga kelompok. Yakni kelompok dosis rendah, dosis sedang, dan dosis tinggi. Masing-masing kelompok 26 orang relawan.
Yang di Amerika baru dicoba minggu lalu. Terhadap 45 orang relawan yang berbadan sehat. Sama dengan yang di Tiongkok: disuntikkan di lengan atas.
Relawan yang sama masih akan dijadikan uji coba kedua: sebulan setelah penyuntikan pertama. Lalu diajukan perizinannya ke FDA –yang biasanya paling cepat 1 tahun.
Akhirnya Trump tahu yang digembar-gemborkannya itu obat malaria zaman dulu. Lantas apa komentarnya?
“Setidaknya sudah diketahui tidak ada yang meninggal akibat obat itu,” katanya.
Seandainya saya terkena Covid-19 dan dokter hanya bisa memberikan Hydrochloroquine-nya Trump atau Avigan-nya Jokowi, saya pun akan meminumnya.
Daripada tergeletak begitu saja di rumah sakit sampai tahun 2021 –saat obat anti Covid-19 dijual kepada masyarakat.
Tapi mengapa saya ikut bicara itu? Seolah itu yang terpenting?
Bukankah yang terbaik adalah mencegah jangan kian banyak yang terkena Covid-19? Dokter yang ada sudah kelelahan. Demikian juga perawat. Bagaimana kalau pasien bertambah terus? Dalam jumlah besar?
Ampuuuuuuun… Dok. Kami seperti sengaja membuat kalian gemetaran menghadapi hari-hari depan. (dahlan iskan)




